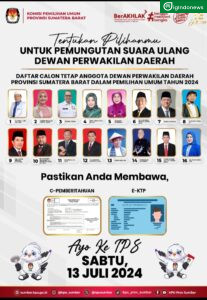Oleh: Robi Alhamda, Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam, UIN SMDD Bukittinggi
Oleh: Robi Alhamda, Mahasiswa S2 Manajemen Pendidikan Islam, UIN SMDD Bukittinggi
Pendidikan: Antara Ideal dan Realitas Sosial
Pendidikan Islam di Sumatera Barat selama ini dikenal berakar kuat pada nilai adat dan agama. Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau dalam membangun peradaban yang religius dan berkarakter. Namun, dalam kenyataannya, sistem pendidikan di daerah ini masih menghadapi ketimpangan yang nyata—baik dalam akses, mutu, maupun keadilan sosial bagi peserta didik.
Sebagai mahasiswa yang menekuni bidang Manajemen Pendidikan Islam, saya melihat bahwa problem utama pendidikan di Sumatera Barat bukan hanya soal infrastruktur dan kebijakan, melainkan juga ketimpangan sosial yang semakin melebar.
Sekolah-sekolah di kota besar seperti Padang dan Bukittinggi berkembang pesat dengan fasilitas modern dan guru berkualitas. Sementara itu, madrasah di nagari-nagari terpencil masih berjuang dengan keterbatasan ruang belajar, tenaga pengajar, dan akses teknologi.
Ironisnya, perbedaan ini berlangsung di daerah yang memiliki sejarah panjang dalam melahirkan ulama, cendekiawan, dan pejuang pendidikan nasional.
Ketimpangan Pendidikan dalam Perspektif Sosiologi
Dalam pandangan Sosiologi Pendidikan, ketimpangan dalam sistem pendidikan mencerminkan ketidakadilan dalam struktur sosial masyarakat.
Pierre Bourdieu menyebut bahwa pendidikan sering kali memperkuat “reproduksi sosial” — di mana kelompok kaya atau berpendidikan tinggi akan terus menikmati akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan, sementara kelompok miskin tertinggal di belakang.
Fenomena ini juga terjadi di Sumatera Barat. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan tinggi mampu bersekolah di lembaga favorit atau boarding school Islam yang lengkap dengan fasilitas digital. Sedangkan di daerah pedalaman, banyak siswa yang masih bergantung pada sekolah konvensional dengan sarana seadanya.
Padahal, semangat pendidikan Islam sejati justru berangkat dari prinsip kesetaraan ilmu: bahwa setiap manusia berhak memperoleh pengetahuan tanpa memandang status sosialnya.
Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-‘Alaq ayat 1–5 bahwa perintah membaca dan menuntut ilmu ditujukan kepada seluruh manusia, bukan hanya kalangan tertentu. Ayat ini mengandung pesan kuat tentang keadilan epistemologis — hak setiap individu untuk belajar dan berkembang secara setara.
Keadilan Pendidikan sebagai Amanah Sosial dan Moral
Keadilan dalam pendidikan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga persoalan moral dan spiritual.
Dalam pandangan saya, pendidikan Islam seharusnya menjadi ruang pembebasan, bukan pengukuhan ketimpangan sosial. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim.” Kalimat “setiap” dalam hadis itu menegaskan bahwa pendidikan harus terbuka bagi semua, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar.
Sayangnya, dalam praktiknya, banyak lembaga pendidikan Islam justru terjebak dalam logika komersialisasi. Sekolah Islam modern kini sering identik dengan biaya tinggi dan fasilitas mewah, seolah mutu pendidikan hanya bisa diukur dengan bangunan megah atau kurikulum internasional.
Saya khawatir, jika pola ini dibiarkan, maka cita-cita pendidikan Islam untuk mencerdaskan umat akan bergeser menjadi bisnis yang mengeksklusifkan akses terhadap ilmu.
Keadilan pendidikan harus dimaknai sebagai tanggung jawab sosial umat Islam. Lembaga pendidikan Islam di Sumatera Barat perlu kembali kepada ruh khidmah — melayani, bukan memperjualbelikan ilmu. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan pengelola sekolah perlu berkolaborasi agar pemerataan pendidikan tidak sekadar slogan, tetapi menjadi gerakan nyata.
Mengatasi Ketimpangan: Peran Sosial dan Kultural Pendidikan Islam
Sebagai orang Minangkabau, saya percaya bahwa solusi ketimpangan pendidikan bisa ditemukan dalam nilai-nilai sosial budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat.
Konsep gotong royong dan musyawarah nagari dapat menjadi basis solidaritas pendidikan. Sekolah-sekolah unggul di kota bisa bermitra dengan madrasah di desa untuk berbagi sumber daya dan pelatihan guru.
Lembaga keagamaan seperti pesantren juga bisa berperan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat—bukan hanya mengajar agama, tetapi juga membantu masyarakat mengakses teknologi dan literasi digital.
Dalam konteks manajemen pendidikan, kita perlu membangun sistem yang berbasis pada prinsip keadilan distributif. Artinya, sumber daya pendidikan (dana, fasilitas, pelatihan guru) harus dialokasikan secara proporsional, bukan berdasarkan lokasi atau status sosial sekolah.
Keadilan bukan berarti semua harus sama, tetapi semua harus mendapatkan kesempatan yang layak untuk berkembang.
Pendidikan Islam di Sumatera Barat memiliki sejarah panjang dan fondasi yang kuat. Namun, tanpa pemerataan dan keadilan sosial, nilai-nilai luhur pendidikan itu akan kehilangan maknanya.
Sebagai generasi muda dan mahasiswa pendidikan Islam, saya berkeyakinan bahwa keadilan pendidikan adalah bagian dari ibadah sosial. Ia bukan sekadar tugas negara, tetapi amanah keagamaan dan moral.
Sudah saatnya lembaga pendidikan Islam di Sumatera Barat bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang mampu memutus rantai ketimpangan.
Karena sejatinya, pendidikan Islam bukan hanya mencetak manusia pintar, tapi membentuk manusia adil — yang sadar bahwa ilmu bukan hak istimewa segelintir orang, melainkan cahaya untuk seluruh umat.