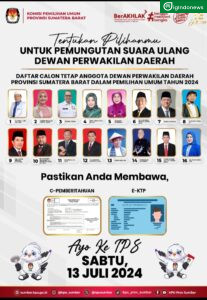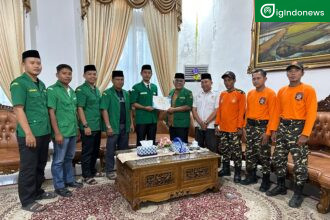Ekonomi
Oleh : Syaiful Anwar
Indikator ini merupakan indicator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan indicator sebelumnya, Indikator memiliki beberapa macam-macam sub- Indikator. Berikut ini adalah uraiannya.
-
Indikator Sosial
Beckerman dalam International Comparisons of Real Incomes (1966) mengelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara ke dalam tiga kelompok: (1) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional. Usaha ini dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh Gilbert dan Kravis (1956), (2) kelompok yang membuat penyesuaian dalam perhitungan pendapatan nasional dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat harga di setiap negara, dan (3) kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (nonmonetary indicators), seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrivikasi, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet.
Menurut Beckerman (1966), dari berbagai metode di atas, metode yang digunakan oleh Gilbert & Kravis (1956) adalah metode yang paling sempurna. Pada metode ini, dilakukan perbaikan pada metode perhitungan pendapatan konvensional dengan menggunakan data pendapatan nasional dari masing- masing negara. Dengan studinya, mereka membandingkan tingkat pendapatan per kapita antara negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Mereka melakukan perhitungan kembali pada pendapatan nasional negara-negara di kawasan Eropa berdasarkan atas tingkat harga di Amerika Serikat. Dengan kata lain, nilai produksi negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat di nilai dengan tingkat harga yang sama. Kesimpulan dari studi yang dilakukan Gilbert & Kravis (1956) adalah bahwa perbedaan tingkat pendapatan per kapita antara penduduk negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Serikat tidaklah sebesar seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan per kapita mereka yang dihitung menurut metode konvensional.
Namun, metode ini memerlukan data yang lengkap dan sering kali data yang diperlukan dalam estimasi tidak tersedia di NSB. Oleh karena itu, Beckerman (1966) mengemukakan metode lain dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara yaitu dengan menggunakan data yang bukan bersifat moneter. Metode ini dinamakan Indikator Nonmoneter yang Disederhanakan (modified non-monetary indicators).
Menurut metode ini, tingkat kesejahteraan dari setiap negara ditentukan oleh beberapa indikator berdasarkan pada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu
yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di NSB. Data tersebut adalah:
- Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg).
- Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton).
- Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun.
- Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10.
- Jumlah persediaan telepon dikalikan 10.
- Jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan.
- Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg).
Usaha lain dalam menentukan dan membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara dilakukan pula oleh United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), sebuah badan PBB yang berpusat di Jenewa pada tahun 1970. Dalam studinya, UNSRID (1970) menggunakan 18 indikator yang terdiri dari 10 indikator ekonomi dan 8 indikator sosial yaitu:
- Tingkat harapan hidup.
- Konsumsi protein hewani per kapita.
- Persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah.
- Persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan.
- Jumlah surat kabar.
- Jumlah telepon.
- Jumlah radio.
- Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih.
- Persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian.
- Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi.
- Persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji atau upah.
- Persentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari industri-industri manufaktur.
- Konsumsi energi per kapita.
- Konsumsi listrik per kapita.
- Konsumsi baja per kapita.
- Nilai per kapita perdagangan luar negeri.
- Produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian.
- Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB).
Jika indeks pembangunan yang diusulkan UNRISD tersebut digunakan sebagai indikator kesejahteraan maka dapat dipastikan perbedaan tingkat pembangunan antara negara-negara maju dan NSB tidaklah terlampau besar seperti yang digambarkan oleh tingkat pendapatan per kapita mereka. Hasil studi UNSRID menyebutkan bahwa dari 58 negara yang dihitung indeks pembangunannya, Thailand merupakan negara dengan indeks paling rendah (10), sementara indeks pembangunan Inggris adalah
- Oleh karena itu, secara relatif dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan Inggris 10 kali lebih besar dari Thailand. Nilai tersebut jelas lebih kecil dari perbandingan pendapatan per kapita kedua negara tersebut. Hasil studi Usher (1963) seperti telah disinggung sebelumnya menyebutkan bahwa perbandingan pendapatan per kapita antara Inggris dan Thailand dengan cara konvensional menghasilkan angka 1 : 13,06. Artinya, pendapatan Inggris adalah 13,06 kali pendapatan per kapita Thailand.
Di antara negara-negara maju, perbedaan tingkat kesejahteraan yang digambarkan oleh indeks pembangunan sering kali lebih kecil dibandingkan jika menggunakan tolok ukur pendapatan per kapita mereka. Misalnya, pada tahun 1970, perbandingan pendapatan per kapita Belanda dan Swedia adalah US $965 dan US $ 1,696, sebuah perbedaan yang sangat besar. Sedangkan perbandingan indeks pembangunan mereka menunjukkan bahwa tingkat pembangunan yang dicapai kedua negara tersebut tidak banyak berbeda yaitu 96 : 103. Kesimpulan yang diperoleh dari studi UNSRID adalah bahwa di banyak negara, pembangunan sosial berlangsung lebih cepat dibandingkan pembangunan ekonominya.
-
Indeks Kualitas Hidup
Pada tahun 1979, Morris D. Morris memperkenalkan satu indikator alternatif dalam mengukur kinerja pembangunan suatu negara yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH) atau Physical Quality of Life Index. Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat kematian bayi, dan tingkat melek huruf.
Berdasarkan setiap indikator tersebut dilakukan pemeringkatan terhadap kinerja pembangunan suatu negara, kinerja tersebut diberi skor antara 1 sampai 100, angka 1 melambangkan kinerja terburuk dan angka 100 melambangkan kinerja terbaik. Untuk indikator harapan hidup, batas atas (upper limit) 100 ditetapkan 77 tahun (harapan hidup tertinggi pada saat studi tersebut dilakukan dicapai oleh Swedia). Sedangkan batas bawah (lower limit) adalah 28 tahun (tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan batas bawah itulah, tingkat harapan hidup suatu negara diperingkatkan dengan skor antara 1 sampai 100. Demikian pula untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya 9 kematian per 1.000 kelahiran (juga dicapai Swedia pada tahun 1973), sedangkan batas bawahnya adalah 229 kematian per 1.000 kelahiran (tingkat kematian bayi tertinggi, di Gabon).
Angka Indeks Kualitas Hidup (IKH) dapat diperoleh dengan rumus:
di mana IHH adalah indeks harapan hidup, IKB adalah tingkat kematian bayi per 1.000 kelahiran, dan IMH adalah indeks melek huruf.
a.Indeks Harapan Hidup dapat dihitung dengan menggunakan rumus
di mana IH adalah harapan hidup per satu tahun kelahiran di suatu negara, 28 adalah tingkat harapan hidup terendah di Guinea-Bissau pada tahun 1950, dan 0,39 adalah angka yang menunjukkan bahwa bila terjadi kenaikan umur harapan hidup sebesar 0,39 tahun, maka akan menghasilkan 1 poin angka indeks.
- Indeks Kematian Bayi dapat di ukur dengan menggunakan formula:
di mana 229 adalah tingkat kematian bayi maksimum (per 1000 penduduk) yang ada di Gabon, 2,22 adalah pembagi yang jika terdapat tingkat kematian bayi terendah yaitu 9 bayi per 1.000 kelahiran, maka akan didapatkan indeks = 100.
- Indeks Melek Huruf (IMH) sama dengan persentase tingkat melek huruf yaitu jumlah melek huruf per 100 orang dewasa.
Kesimpulan umum yang didapat dari studi Morris (1979) adalah bahwa negara-negara dengan pendapatan per kapita yang rendah cenderung memiliki IKH yang rendah pula. Namun, hubungan antara pendapatan per kapita dan IKH tidak selamanya searah. Sejumlah negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru malah memiliki IKH yang rendah, bahkan lebih rendah dari IKH negara-negara miskin. Di sisi lain, sejumlah negara dengan jumlah pendapatan per kapita yang rendah justru memiliki IKH yang lebih tinggi dari negara-negara berpenghasilan menengah ke atas.
Secara umum, Tabel 1.3 menunjukkan bahwa IKH untuk kelompok negara-negara maju jauh lebih tinggi dari IKH kelompok NSB. Namun di sisi lain, dari data tahun 1970 sampai 1990 memperlihatkan bahwa variasi kenaikan skor IKH untuk NSB cukup signifikan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan “kualitas hidup” penduduk di NSB. Sementara itu, Tabel 1.4 menunjukkan tren IKM di beberapa propinsi di Indonesia pada periode 1970-1990.
Tabel 3.3
Trend Indeks Kualitas Hidup (PQLI) pada 10 Negara
| Negara | 1970 | 1980 | 1990 |
| Kelompok NSB: | |||
| Tanzania | 43 | 48 | 53 |
| Ethiopia | 31 | 35 | 46 |
| India | 44 | 49 | 59 |
| Indonesia | 55 | 62 | 74 |
| Brazil | 68 | 70 | 77 |
| Kelompok Negara Maju: | |||
| Jepang | 92 | 94 | 95 |
| Kanada | 91 | 92 | 94 |
| Inggris | 90 | 92 | 93 |
| Amerika Serikat | 91 | 92 | 93 |
| Belanda | 92 | 93 | 94 |
Sumber : Nick van der Lijn, Measuring Well-Being with Social
Tabel 3.4
Tren Indeks Kualitas Hidup (PQLI) di Indonesia
| No. | Propinsi | 1970 | 1980 | 1990 |
| 1 | Aceh | 50 | 64 | 78 |
| 2 | Sumatera Utara | 58 | 68 | 79 |
| 3 | Sumatera Barat | 50 | 57 | 75 |
| 4 | Riau | 54 | 59 | 77 |
| 5 | Jambi | 44 | 56 | 74 |
| 6 | Sumatera Selatan | 47 | 64 | 75 |
| 7 | Bengkulu | 46 | 59 | 75 |
| 8 | Lampung | 48 | 63 | 75 |
| 9 | DKI Jakarta | 54 | 72 | 86 |
| 10 | Jawa Barat | 43 | 53 | 68 |
| 11 | Jawa Tengah | 42 | 59 | 73 |
| 12 | D.I. Yogyakarta | 41 | 69 | 80 |
| 13 | Jawa Timur | 44 | 57 | 72 |
| 14 | Bali | 42 | 59 | 76 |
| 15 | NTB | 30 | 31 | 47 |
| 16 | NTT | 45 | 51 | 58 |
| 17 | Kalimantan Barat | 42 | 51 | 67 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 53 | 63 | 79 |
| 19 | Kalimantan Selatan | 48 | 57 | 69 |
| 20 | Kalimantan Timur | 52 | 62 | 79 |
| 21 | Sulawesi Utara | 62 | 69 | 80 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 49 | 56 | 69 |
| 23 | Sulawesi Selatan | 38 | 54 | 71 |
| 24 | Sulawesi Timur | 36 | 54 | 70 |
| 25 | Maluku | 51 | 51 | 74 |
| 26 | Irian Jaya | – | 57 | 64 |
Sumber: BPS 1992